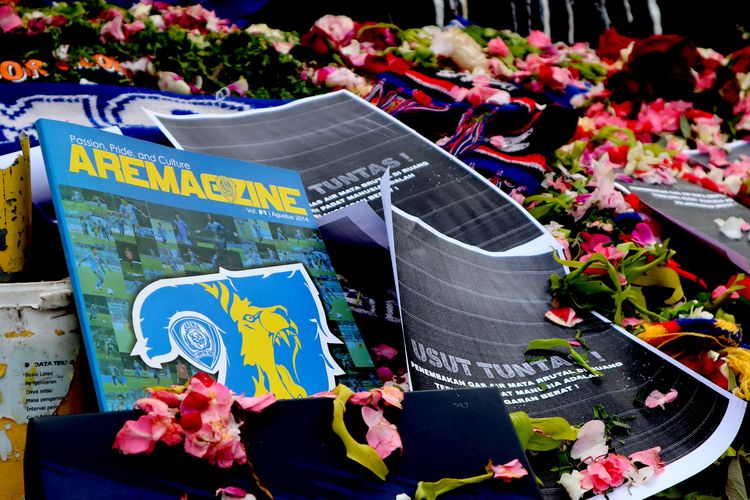tentang.co.id – Berpulangnya Ratu Elizabeth II pada 8 September 2022 akan dikenang dalam catatan sejarah sebagai salah satu kematian pemimpin bangsa paling menyita perhatian dunia.
Meninggal pada usia 96 tahun, Ratu Elizabeth naik takhta pada 2 Juni 1953.Selama 70 masa pemerintahannya, Sang Ratu telah menjadi saksi berbagai momen bersejarah di dunia, termasuk saat Inggris memenangkan Piala Dunia pertama dan satu-satunya – setidaknya hingga saat ini – pada 1966.
Terkait sepak bola, seluruh klub yang ada di Inggris Raya pun turut mengucapkan bela sungkawa melalui berbagai platform media yang dimiliki, khususnya media sosial, tak lama setelah pengumuman meninggalnya Ratu Elizabeth II.
Ucapan-ucapan tersebut memang menjadi ‘penting’ dan juga ditunggu mengingat Inggris merupakan kiblat dari salah satu olahraga paling populer di dunia tersebut.
Namun, ada yang ‘menarik’ dan mungkin sesuai prediksi dari para pecinta sepak bola Inggris yang sedikit mengetahui sejarah hubungan klub dengan Kerajaan.
Liverpool, klub Inggris tersukses dari total raihan trofi, menjadi klub terakhir yang mengucapkan belasungkawa melalui akun sosial medianya.
Di Twitter, dari 20 klub yang berada di kasta tertinggi Liga Inggris, 19 klub yang perlu sekitar 30-60 menit untuk mengucapkan bela sungkawa. Lain halnya dengan Liverpool yang ‘membutuhkan’ waktu lebih dari 2 jam untuk mengucapkan hal serupa dengan disertai foto pada 1965 kala Sang Ratu memberikan Piala FA kepada kapten Liverpool saat itu, Ron Yeats.
Selain mengucapkan belasungkawa, para klub Liga Premier juga mengganti foto profilnya masing-masing dengan latar belakang hitam dan logo klub berwarna putih. Bisa ditebak, Liverpool jadi tim terakhir juga yang mengganti foto profilnya tersebut.
Terlepas dari tim sosial media Liverpool yang kurang gercep, momen ‘kebetulan’ tersebut bisa jadi pengingat bahwa Liverpool, baik sebagai klub sepak bola maupun kota, berbeda dengan kota lainnya di Inggris.
Sejarah panjang mewarnai perjalanan Liverpool yang kerap berselisih dengan penguasa Inggris, termasuk para perdana menterinya yang menjalankan pemerintahan.
Liverpool adalah kota pelabuhan di wilayah Merseyside, bagian Barat Laut Inggris. Pelabuhan di kota ini sempat diklaim menjadi yang terbesar setelah London dan salah satu pelabuhan kargo utama di dunia.
Penduduk di kota ini pun cenderung unik dan berbeda dibandingkan dengan kota-kota lain di Inggris. Aksen para Scouser, julukan orang-orang asli dari wilayah ini yang pertama kali ‘diakui’ pada 1959, dianggap aneh, bahkan oleh orang-orang Inggris sendiri.
Tak jarang ejekan ndeso disematkan pada orang-orang Liverpool dengan aksen Scouse-nya. Namun, warga Merseyside justru seringkali menunjukkan kebanggaannya dengan menyatakan bahwa mereka bukan orang Inggris, melainkan Scouse.
Dengan ‘stempel’ berbeda dibandingkan dengan kota-kota lain, ditambah dengan statusnya sebagai kota pelabuhan yang memungkinkan banyak imigran datang dengan budayanya masing-masing, Liverpool memang beda dengan kota-kota kain di Inggris.
Sejalan dengan hal tersebut, cara pandang masyarakat kota ini pun menjadi agak lain, dan seringkali tak sepaham dengan kebijakan konservatif kerajaan dan pemerintahan.
Alhasil, Partai Konservatif yang telah sekian lama menguasai pemerintahan Inggris tak laku di sana. Sebaliknya, Partai Buruh yang berhaluan kiri mendominasi di Liverpool.
Ketegangan antara Liverpool dengan pihak pemerintahan Inggris meruncing pada era akhir 19780an-1980an kala kota pelabuhan itu mengalami krisis. PHK besar-besaran tak bisa dihindari dan aktivitas dermaga turun signifikan.
Kondisi tersebut yang meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran, langsung menjadi ladang subur bagi Partai Buruh untuk meraup suara di wilayah tersebut.
Sudah jatuh tertimpa tangga, gejolak yang dialami saat itu pun diperparah oleh meletusnya kerusuhan Toxteth, sebuah distrik di pusat Liverpool, pada 1981 yang melibatkan polisi setempat dengan komunitas kulit hitam.
Melansir BBC, berdasarkan dokumen pemerintah yang dirilis di bawah aturan 30 tahun menunjukkan bahwa para politisi Partai konservatif mendesak Perdana Menteri (PM) Inggris saat itu, Margaret Thatcher, untuk tidak menghabiskan uang publik di ‘tanah berbatu’ Merseyside.
Padahal, sebelumnya telah ada rencana untuk pemulihan kota dengan diutusnya Menteri Lingkungan Michael Heseltine ke Liverpool. Namun, di balik layar di Whitehall, tokoh senior lainnya segera meragukan rencana ambisius Heseltine.
“Kami tidak ingin menemukan diri kami memusatkan semua uang tunai terbatas yang mungkin harus disediakan ke Liverpool dan tidak memiliki apapun yang tersisa untuk area yang mungkin lebih menjanjikan seperti West Midlands atau, bahkan, Timur Laut,” kata surat yang ditulis Kanselir Perdana Menteri saat itu Sir Geoffrey Howe.
Di tengah berbagai desakan tersebut, The Iron Lady, julukan Thatcher, akhirnya ‘mendiamkan’ kota Liverpool berjuang sendirian menghadapi krisis yang terjadi.
Tak hanya itu, sikap Thatcher terhadap tragedi Heysel dan Hillsborough, kerusuhan berdarah yang melibatkan pendukung klub Liverpool, juga menggoreskan luka di hati para Liverpudlian.
Dalam tragedi Hillsborough yang terjadi pada 15 April 1989 itu, Liverpoll tengah berdahadapn dengan Nottingham Forest dalam partai semifinal Piala FA.
Suporter membludak dan berdesak-desakan. Sebanyak 97 orang pendukung Liverpool tewas, di mana yang terakhir meninggal pada 26 Juli 2021 lalu karena sakit yang diderita akibat kejadian 3 dekade lalu itu.
Thatcher, seperti politisi Inggris lainnya, cenderung menyalahkan suporter Liverpool yang dianggap barbar. Media pun menyudutkan Liverpudlian, terutama The Sun, hingga memicu kemarahan warga di kota tersebut sampai ada ajakan untuk tak membeli surat kabar itu lagi (don’t buy The Sun).
Namun, perjuangan panjang suporter Liverpool akhirnya terbayar pada 2016. Setelah dilakukan penyelidikan baru pada 2012, Pengadilan Tinggi London akhirnya menyatakan kesalahan ada pada pemimpin kepolisian yang gagal dalam mengatur aliran penonton ke stadion.
Lalu, setelah melewati masa pemerintahan Thatcher ketegangan mereda? Tampaknya tidak.
Mantan PM Boris Johnson, yang baru saja lengser digantikan Liz Truss, juga memiliki hubungan buruk dengan Scousers.
Melansir Liverpool Echo, Johnson yang pernah menjadi editor Spectator, dianggap meloloskan kata-kata memalukan untuk dipublikasikan tentang Scousers yang bekerja keras, keluarga korban Hillsborough, dan Ken Bigley, insinyur Liverpool yang dibunuh secara brutal di Irak pada tahun 2004.
Di luar gejolak politik ekonomi, puncak dari ketegangan Liverpool dengan Pemerintah dan Kerajaan Inggris, sekaligus olok-olok paling ‘pedas’ justru datang dari lapangan hijau.
Pada 4 Agustus 2019, misalnya, kala Liverpool menghadapi Manchester City dalam laga Community Shiled di Stadion Wembley, London.
Ketika lagu kebangsaan, God Save The Queen dinyanyikan, para pendukung Liverpool justru memberikan sikap tak hormat dengan menyorakinya tepat di hadapan anggota kerajaan yang saat itu diwakili Pangeran William.
Hal serupa juga terulang baru-baru ini, pada 30 Juli 2022, juga dalam laga Community Shield yang mempertemukan Liverpool dan Manchester City di King Power Stadium. Liverpudlian kembali mencemooh lagu kebangsaan God Save The Queen.
Kini Sang Ratu telah berpulang dan lagu kebangsaan berubah menjadi God Save The King. Perubahan kecil itu jelas bukan jaminan bahwa ‘perlawanan’ Scousers dari tribun lapangan hijau akan terhenti.